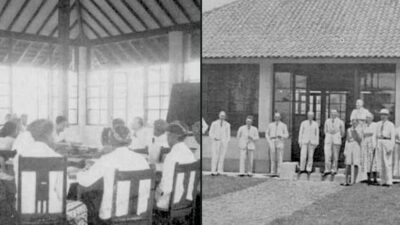gkjw.org -Berbicara tentang agama dan kehidupan beragama di Indonesia memang tak akan pernah ada habisnya. Sudah saatnya ketika berbicara tentang agama, kita memakai kacamata yang berbeda dari yang selama ini kita pakai, dengan kata lain, melihatnya haruslah dari berbagai sudut pandang. “The Meaning and The End of Religion” karya Wilfred Smith mungkin bisa membantu bagaimana kita memahami makna agama secara holistik. Peradaban Timur (Cina dan India terutama) dan Barat dengan berbagai budayanya, yang didalamnya juga termasuk agama, seiring berjalannya waktu akhirnya sampai juga di Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri bahwa itu juga turut ikut andil dalam membentuk pola pemikiran sebagian besar rakyat Indonesia. Di tahun 2010, data yang di peroleh oleh BPS melalui sensus penduduk mengatakan 87% masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, kemudian 6,9% Kristen Protestan, lalu 2,9% Kristen Katolik, dilanjutkan 1,7% Hindu, disusul Buddha dengan 0,7%, ada Konghucu 0,05%, dan sisanya adalah mereka yang tidak mengasosiasikan diri dengan ke-6 agama tersebut, dan sudah dipastikan bahwa beberapa dari mereka adalah para pemeluk agama suku.
2 – Memandang Matahari 2 – Memandang Matahari
3 – Becik Ketitik "Gendheng" Ketara 3 – Becik Ketitik "Gendheng" Ketara
Disadari atau tidak, kehadiran agama-agama besar dunia ke Indonesia, seperti Kekristenan yang datang bersamaan dengan kolonialisme, membawa pemikiran-pemikiran yang sarat dengan paradigma dunia Barat, salah satunya adalah pola pikir dualistik. Dualisme, yang oleh Cambridge Dictionary diartikan sebagai sebuah keyakinan dimana segala sesuatu dibagi menjadi dua yang seringkali sangat berbeda dan bertentangan, adalah corak pemikiran yang mau tidak mau harus kita akui sudah mengakar rumput pada rakyat Indonesia. “Aku benar, selain aku salah”, “Yang kusembah hanya satu Tuhan, mereka menyembah lebih dari satu berarti dosa”, “Yang aku imani adalah yang tidak kelihatan dan tidak berbentuk, mereka yang menyembah yang nampak berarti mereka menyembah berhala”, simplifikasi seperti ini akhirnya secara tidak langsung menimbulkan perasaan superior dalam diri kita, para pemeluk agama Abrahamik, sehingga dengan gampangnya melabeli siapa-siapa yang tidak ‘seiman’ dengan kita adalah yang sesat.
Bersumber dari pola pikir dualistik yang rasional inilah agama atau religi juga dimaknai secara berbeda. Agama, yang dalam bahasa Inggris disebut religion, bersumber dari bahasa Yunani , “religio”, mengalami pergeseran makna dari waktu ke waktu. Kitab suci, ritual, punya tokoh utama, dan selalu mengandung konsep teologis adalah makna agama yang dipahami sebagian orang pada masa pencerahan di Eropa. Religio pada mula-mula tahun masehi dipahami menjadi dua hal, yaitu pertama, religiosae locate (lokasi religius) yang dimaknai sebagai kekuatan yang suci, atau juga sebuah tempat suci yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki daya atau kemampuan untuk membuat individu melakukan sikap-sikap tertentu, dan kedua, viri religiosi yang merujuk pada sikap individu terhadap kekuatan yang suci itu. Dari dua hal inilah, masa awal Kekristenan muncul, makna religio mengalami pergeseran menjadi religio dei, atau cara penyembahan terhadap satu Tuhan, dan pemahaman semacam ini akhirnya membuat Kekristenan menjadi paling unggul dan merasa sebagai yang paling benar pada masa itu.
Pada abad ke-5, St. Agustinus, seorang ‘pemuka’ dari Kekristenan, berpendapat bahwa religio adalah ikatan manusia secara personal dengan Yang Ilahi atau yang disebut Tuhan itu. Selanjutnya, di abad 11 dan berakhir pada abad 14, religio dipahami sebagai ikatan manusia dengan Tuhan, namun secara spesifik dalam lingkup kehidupan monastik. Abad 15, adalah masa dimana Eropa menghidupi budaya Helenis, religio dimaknai sebagai ‘insting’ manusia untuk mencari kekuatan yang suci dan juga sebagai sikap untuk menyembah Tuhan. Selanjutnya pada masa Reformasi Kekristenan yang dilakukan oleh John Calvin, religio atau disebut juga religio ney adalah ajaran-ajaran yang mengajarkan kesalehan berdasarkan tradisi-tradisi iman Kristen. Masuk pada masa pencerahan (abad 17), dimana rasionalisme menguasai Eropa, religio atau religio ney dipahami sebagai sebuah sistem kepercayaan yang benar, dimana Kekristenan masih merasa bahwa ia adalah realitas yang paling benar, serta realitas lain adalah rivalnya, dan rupanya pemaknaan terakhir inilah yang dipakai hingga detik ini.
Kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat kepada bangsa-bangsa di Timur ternyata menggiring idealisme Barat seperti diatas bertemu dengan realitas Timur yang begitu plural, pertemuan inilah yang kemudian menjadikan religio berubah makna, dari religion menjadi religions. Pertemuan Kekristenan dengan Hindu dan Buddha dengan dharma-nya, dengan Shinto, atau prinsip Yang-Yin khas Konghucu dan Tao. Secara khusus di Indonesia bersentuhan dengan jutaan agama suku di Indonesia dengan nilai-nilai luhur yang ada pada mereka, seperti Kaharingan di Kalimantan dengan konsep Petak Tapajakan yang mengajarkan bahwa bumi ini adalah tempat dimana kita memuliakan Yang Ilahi dengan perbuatan baik kita, juga kepercayaan Uis Neno dari Suku Boti di NTT dengan salah satu ajarannya yang mewajibkan individu menjaga hutan, karena hutan adalah rumah, dimana menyakiti hutan sama artinya dengan menyakiti diri sendiri, atau berbagai aliran Kebatinan yang masih banyak dihidupi oleh masyarakat Jawa. Mengutip pernyataan Wilfred Smith, makna religio ataupun religion sebagaimana yang dipegang teguh oleh bangsa Barat tidak memiliki padanan kata yang sesuai dengan realitas di Timur, dimana agama bukan lagi sebuah sistem yang berada diluar diri manusia. Di China, dari buku “The Meaning and The End of Religion”, dikatakan bahwa orang yang bukan berasal dari Cina akan sangat heran ketika melihat orang Cina bisa ‘memeluk’ Buddha, sekaligus mengamalkan nilai-nilai luhur dari Konfusius atau KongHucu, namun juga menghidupi ajaran Taoisme, dan itu adalah hal yang biasa. Praksis hidup semacam itu bukankah juga ada di bumi Pancasila ini? Lalu apa yang salah? Agama di Timur bukanlah sesuatu yang final, bukan “titik” melainkan “koma”, agama adalah proses, bukan sebagai yang mengikat namun sebagai yang menuntun manusia pada kebajikan, dan maka dari itu agama nampak begitu fleksibel, cair, dan inklusif sehingga meminimalisir terjadinya konflik.
Nahasnya, durasi kolonialisme bangsa Barat di Timur, terkhusus di Indonesia, memakan waktu yang begitu lama, hingga meski secara fisik mereka tak lagi menjajah Ibu Pertiwi, namun jejak-jejak hegemoni itu masih terasa meski 75 tahun kita sudah merdeka, dan keadaan ini akan semakin langgeng apabila pemeluk agama-agama ‘besar’ yang tak kunjung menyadari identitas mereka dan masih memaksakan kacamata khas Barat untuk melihat realitas plural bangsa ini dan membuat saudara seIbu Pertiwinya terjajah. Kemerdekaan kita, kebebasan kita, keleluasaan kita, benarkah itu juga memerdekakan sesama kita? Sudahkah membawa damai sejahtera bagi sesama? Atau malah membuat sesama terluka dan terpenjara dalam rasa bersalah dan berdosa karena tidak sama dengan kita? Merdeka, mari juga dilihat secara holistik.
Menutup risalah ini, saya pribadi teringat akan khotbah malam kemerdekaan pada Minggu, 16 Agustus 2020 yang lalu dari salah satu pendeta GKJW, yaitu Pdt. Yuli Erna Wati , “di tahun ke-75 negara ini merdeka, mari juga kita merdeka (merdeka = merengkuh dengan kasih)”. Merdeka!
Oleh : Oktavia Yermiasih
Gambar Ilustrasi :
wwwhttps